Seni dalam Tiga Dimensi Epistemologi
Oleh: M Taufan Musonip
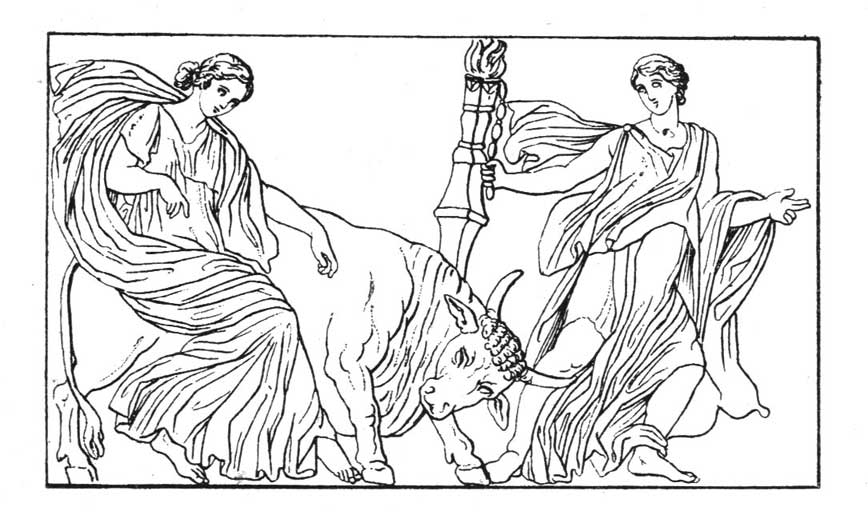 |
| gis.com.qa |
Jika sintesa tetang seni sedemikian mempengaruhi kejiwaan manusia, maka
seni merupakan satu media yang tak bisa direndahkan di antara sub bidang
keilmuan lainnya. Oleh karena seni adalah jiwa manusia, maka eksistensinya
dapat memberi penerang eksistensi sub bidang keilmuan lainnya. Mungkin kita sering
mendengar ungkapan-ungkapan yang menggandeng seni dengan aktifitas keilmuan
lainnya seperti seni perpolitikan, seni desain dan teknologi, hingga seni
beragama.
Jika seni sebagai objek yang menjelaskan eksistensi kemanusiaan, maka
paradigma kita melihat seni perlu dikaji ulang. Ini merupakan satu tesis yang menyatakan seni dapat bergeser tergantung
siapa yang mengerjakan objek seni, artinya apakah eksistensi seni itu hanya
berakhir pada kedirian si pelaku seni atau dapat menembus batas eksistensi dan
kedirian pelaku seni. Jika seni hanya berakhir pada kedirian si pelaku, maaf,
maka seni baru bersifat memaknai sifat kebinatangan si pelaku. Seni sering
dibatasi oleh sifat-sifat egosentrik si pelaku, karena jika tidak, maka
hilanglah sifat ke-adiluhungan suatu karya seni, seni sering hanya dapat dibaca
oleh kalangan yang mengerti seni itu sendiri.
Identifikasi manusia yang tak dapat mengerti arti sebuah seni yang dibuat
si pelaku, adalah dampak kungkungan egosentris terhadap karya seni yang dibuat.
Dalam hal ini muncullah dikotomi seni rakyat dan seni adiluhung. Seni yang
dapat dimengerti oleh banyak orang dan seni yang hanya dimengerti oleh beberapa
orang.
Namun jangan dulu miris terhadap kata sifat kebinatangan yang tertuang
dalam sebuah karya seni, karena pada dasarnya seni adalah sifat duniawi. Sebuah
makna yang disebut Nietzsche sebagai semangat Apolonian, yaitu upaya
penggambaran dunia yang absurd, immoral, Nafsu hingga dendam. Banyak karya seni
yang memuat hal ini, seperti bangunan piramida di mesir, taman gantung di Mesopotamia dan banyak lagi yang gambarannya hanya dapat
dimengerti oleh beberapa orang yang mengerti esensi seni sekaligus sebagai
sebuah ciri eksistensi kebesaran satu komunitas manusia. Bukankah manusia itu
memendam sifat kebinatangan?
Kalau kita melihat seni sebagai sebuah objek yang dapat diteliti
maknanya, maka ia sesungguhnya berdiri dalam dua tesis yang memaknai eksistensi
manusia itu sendiri, saya melakukannya melalui tesis yang dirunut Muthahhari
dan Nietzsche tentang insan. apa bedanya manusia dan Hewan?
Pertanyaan itu pastilah berujung pada subtansi tentang tujuan. Nietzsche
bahkan menyebut turunnya harkat manusia menjadi cenderung binatang jika ia tak
dapat merealisasikan tujuannya. Sementara Muthahhari, melampaui pengertian Nietzsche
bahwa tujuan itu bertingkat-tingkat, hewan hanya memiliki tujuan yang di batasi
oleh batas-batas naluriah, karena hewan hanya memiliki utilitas inderawi dalam
menyikapi kehidupannya.
Oleh karenanya mereka sepakat, bahwa bila manusia ingin menempuh tujuan
manusiawinya maka metodologi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan utilitas
yang melampaui kesadaran empirik dalam menciptakan kebutuhannya, ia adalah akal
yang terdiferensiasi dalam kehendak logosentrik dan rasional. Sebuah kehendak
yang digambarkan sebagai semangat dionisian. Artinya jika apolinian
menggambarkan kengerian hidup yang tergambar dalam keindahan dunia, maka
Dionisian adalah semangat ego dalam menyikapi gambaran kehidupan tersebut.
Disini eksistensi seni masih
menggambarkan manusia sebagai hewan rasional.
Bagaimana seni dapat mencitrakan si pelaku sebagai manusia sejati? Adalah
ketika seni dapat sublim dalam hiruk pikuk manusia, berarti seni sudah diwarnai
oleh kehendak intuitif.
Kehendak intuitif itu mencerminkan semangat nihilisme seperti pendapat
Nietzsche dan dimensi esoterik menurut para sufi. Sebuah semangat yang
sebetulnya mengandung makna ketaktergantungan manusia terhadap apapun namun
akhirnya harus dapat sublim dimata khalayak.
Nihilisme dan dimensi esoterik ---meskipun tak percis sama namun
mengandung makna yang analog--- adalah kegiatan berkesenian yang tercipta
berdasarkan keinginan melakukan perubahan, meskipun harus sublim, tak berarti
seni hadir sebagai tuntutan apapun (masyarakat, pasar), namun merupakan sebuah
karya yang melambung menembus zaman kini, sebagai solusi kehidupan
bermasyarakat, oleh karenanya dapat dimengerti ---Apakah dengan ini kita dapat
merubah paradigma pemikiran Nietzsche yang awalnya kita nisbatkan sebagai tak
bertuhan, menjadi bertuhan?. Tentunya tindakan ini radikal. Namun jika kita
melihat paradigma beragama sebagai sebuah tindakan kehidupan yang tak
tergantung pada apapun maka sebutan Nietzsche ateis dapat kita pertimbangkan
lagi.
Jika Seni adalah ending dari
kegiatan kontemplasi si pelaku seni, maka semangat Nihilisme dan esoterik
adalah kondisi dekadensi (keruntuhan) nilai-nilai duniawi menuju kekosongan,
bumi yang merupakan eksistensi wujud menjadi terbalik: bumi dan raga manusia
serta apa yang dapat kita lihat menjadi wujud non eksitensi, sedang dunia ghaib
atau apa-apa yang tak dapat kita lihat, disebut
sebagai eksistensi, nah jika pengalaman intuitif ini terjadi, maka seni akan
eksis bukan hanya melalui tindakan empirik dan rasionalitas tapi terlebih suprasensorik.
Dengan demikian seni merupakan wujud yang teremanasi oleh unsur ketuhanan, yang
ditankap oleh indera supra sensorik pada saat melakukan kegiatan kontemplasi.
Seperti halnya pemikiran Netzsche tentang Nihilisme, para sufi pun
sependapat bahwa utilitas epistemologi tersebut tak dapat menjadi wahana
ketergantungan manusia. Rasionalitas, empirik, dan intuisi adalah
instrumen-instrumen yang hanya dapat mengantarkan manusia mengetahui alam
hakikat (keghaiban), melalui metodologi-metodologi yang sekali lagi dapat
menjadikan manusia menempati kesempurnaanya, bahkan para sufi menyebutnya
sebagai manusia yang dapat “manunggaling
kaula gusti” (bisakah di analogikan dengan ubermencsh-nya Nietzsche?).
Bukankah Ketergantungan itu hanya pada Allah?,
Oleh karena itu seni dapat dijadikan simbol dalam hal memuat kebesaran
Allah, baik secara transedental, maupun imanen. Seni merupakan media kebesaran
manusia sebagai khalifatullah disamping merupakan pembuktian eksistensi Tuhan
dalam hal menyampaikan kebenaran-Nya. Seni harus dapat dimengerti melalui
aktifitas raga dan intuisi, untuk mengakui ketergantungan kita kepada-Nya.
Pertanyaannya terakhir adalah mengapa seni terkadang sulit dipahami?, karena
para pelaku seni sekarang kurang melakukan sosialisasi bagaimana memahami karya
seni. Sehingga para penikmat seni hanya memandang seni dalam satu dimensi saja,
rasionalisme semata, empirik semata, intuisi semata. Seni rakyat bukan berarti
seni yang hanya dapat dipahami oleh satu dimensi epistemologi, tetapi merupakan
sebuah karya seni yang dapat memberi inspirasi perubahan bagaimana pemahaman
epistemologi dapat dimengerti. Seperti halnya kita dapat membaca Cerpen Sunda
karya Ajip Rosidi, berjudul Dorma
Ngabasmi Komunismeu (Dorna Membasmi Komunisme), dan cerpen-cerpen karya
Godi Suwarna, yang menceritakan bagaimana imaji intelektual dapat mewarnai
cerita-cerita legenda (lokal) daerah, dengan bahasa yang mudah dipahami
masyarakat awam sekalipun (seperti cerpennya: Kalangkang Budah/ Bayangan buih: sebuah karya yang menginspirasi
bagaimana legenda Oddipus memiliki kemiripan jalan cerita dengan legenda
Sangkuriang, keduanya sama-sama tertarik oleh kecantikan sang ibu).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar