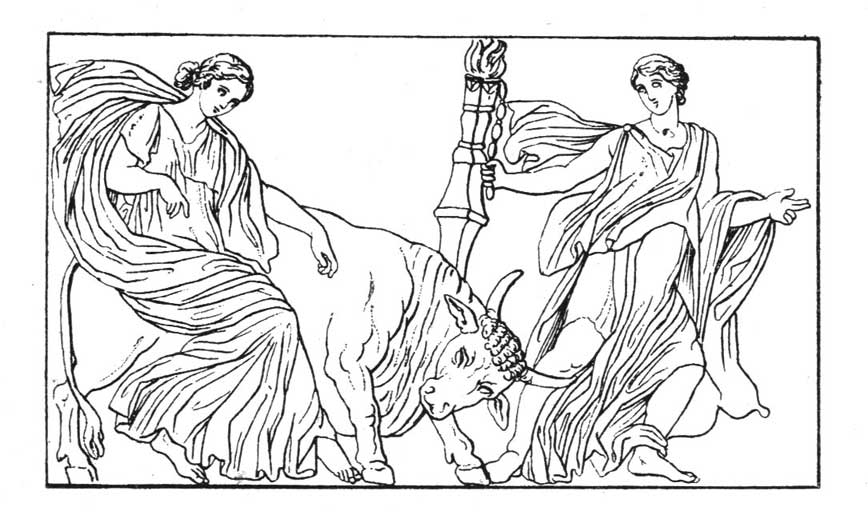Kematian Jaman dalam Kalapati
Telaah untuk Buku Kumpulan Carpon Hadi AKS*
Oleh: M Taufan Musonip
Jalan kematian yang direnda oleh Hadi AKS dalam kumpulan carpon (cerpen)
berjudul Kalapati begitu cekam. Kala berarti waktu dalam bahasa
Indonesia, wanci dalam bahasa Sunda,
atau lebih makro lagi: zaman, sedangkan kata pati, dalam bahasa Indonesia bisa disebut mati, atau kematian.
Secara mikro Kalapati mungkin mewakili kisah seorang anak yang orangtuanya mati
karena diduga sebagai dukun teluh di sebuah
desa yang sedang diburu oleh isu santet (Kalapati,
hal. 45).
Secara keseluruhan dari dua belas
kisah pendek itu saya membacanya sebagai zaman kematian, atau bisa dibalik
menjadi semacam kematian zaman yang mewakili kehidupan hari ini. Hadi AKS,
hidup di zaman di mana modernitas mendesak lokalitasnya sendiri sebagai urang
sunda. Keterdesakan itu memaksa Hadi untuk mengisahkan hidup manusia Sunda kiwari dalam bencana demoralisasi.
Kalapati, bisa
direfleksikan dalam nafas filsafat nihilisme, yang destruktif, tragik, penuh
cekam. Dari sanalah sebenarnya eksistensi seorang manusia dipertanyakan. Tapi
bagi Hadi, tragedi merupakan bagian dari estetika itu sendiri, selain
keteraturan. Maka dalam hal ini pengarang mengeksploitasinya, meski mungkin
keadaan itu bukan suatu hal yang dikehendaki.
Karenanya kemudian oleh pengarang
pembaca dibawa kepada kenyataankenyataan pahit, tentang incest, keinginan bunuh diri, kebencian terhadap orang tua, kesendirian,
kegelisahan, kecemasan, dan kerusakan lingkungan yang menelusuri jalan pada
kematian. Bagai martil yang memorak-porandakan kehidupan manusia lokal masa
lalu sebagaimana diungkapkan dalam Lemah
Cai Kulup (Hal.7):
“Bangsa urang mah, barudak, komo urang Sunda, katelah luhung budi. Béar
daréhdéh, someah hadé ka semah. Titih rintih salawasna, dina ucap jeung
paripolah,”
Tangan Tak Terlihat
Orang lokal yang pada kenyataannya
memiliki budi baik pada tiap pendatang, yang menghayati benar kebersamaan,
tergerus oleh sesuatu yang baru, datang dari berbagai perangkat modernitas, memecah belah kebersamaan, menuju cacahcacah
individu yang tak pernah tahu keakuannya. Bagi Hadi modernitas semacam
ketaksempatan manusia untuk sejenak berpikir, menentukan pilihan hidupnya,
menyadari dirinya sebagaimana manusia yang dapat menghayati kemanusiaannya.
Itu tergambar dalam kecekaman
tokoh-tokoh yang diciptakan pengarang, Acéng yang melakukan pengejaran terhadap
jaringan sindikat penjualan anak, untuk mencari adiknya, yang dijual ibunya sendiri
dalam Basa Lambak Cahayaan (hal. 27).
Seorang wanita muda dalam bayangbayang ketakutan oleh berbagai hal yang
melingkupi dirinya, kehamilan sebagai buah dari hubungan terlarang incest dengan kakak kandungnya sendiri dan
kengerian buasnya alam semesta dalam bencana meluapnya sungai Citarum di mana
wanita itu tinggal bersama abangnya(Sarah, hal. 18). Atau perceraian yang
terjadi pada pasangan muda, sebagai korban dampak kebijakan politik
transmigrasi, dalam Kalakay (hal.58).
Bayang-bayang mitos kala dalam Kala (hal.38) yang terseret arus modernitas yang serba rasional, namun
tak bisa menjawab kesialan pada orang-orang yang tak beruntung, bagai sengaja
dipertahankan, untuk mengukuhkan kemenangan sekelompok orang, sambil terus
menertawakan mitos, sebagai cara mengekpresikan kekalahan, kala adalah ilmu
perbintangan kuno urang sunda, yang menjadi petunjuk bagi perjalanan manusia.
Lain hal dengan kisah Kampung Samada
(hal. 102), tiga bersaudara yang dicacah oleh wasiat seorang ayah. Wasiat itu
disampaikan secara berbeda pada masing-masing anak, tentang di mana jenazah
harus dikuburkan. Karena mempertimbangkan tokoh utama (aku) sebagai anak cikal
yang menerima wasiat penguburan di dalam hutan, maka tiga bersaudara bersepakat
menguburkan jenazah di dalam hutan. Mayat itu kemudian mengalami pelapukan,
menjadikan hutan semakin sejuk dan subur, yang pada puluhan tahun setelah itu
menjadi tempat hidup seluruh warga keturunan Ki Samada (nama tokoh ayah),
sebagai awal malapetaka banjir dan longsor yang memakan banyak korban penduduknya karena terjadi penggundulan hutan.
Kisah-kisah itu memautkan nihilisme
dalam perburuannya terhadap nalar, sebagaimana dilukiskan oleh Nietzsche, dalam
aforisme perjalanan manusia di atas seutas tali, yang begitu ngeri di intai bayang-bayang
kejatuhan, perhentian yang lebih mematikan, dan jalan kembali yang lebih
berbahaya. Sehingga hidup tak lagi mempertanyakan apa yang harus dilakukan,
seperti seseorang yang tengah terkapar tertembus anak panah dari pemanah yang
tak tahu muasalnya, untuk melupakan pencarian kepada si pembunuh, kecuali
mencabut anak panah itu sendiri. Keadaan yang serba salah ini membuahkan
tragedi, pesimisme, dekadensi, dari intaian kuasa tangan tak terlihat otoritas agama, modal, kekuasaan, mitos
yang kemudian menciptakan ketakmampuan berkomunikasi dengan kuasa itu sendiri,
kecuali menjalani hidup tanpa memberi kesempatan pada nalar untuk menghujah
keadaan sebagaimana harapannya.
Mobil Sejarah
Bagi Hadi lokalitas tak lain
merupakan bagian masa lalu dalam mobil sejarah yang sesekali melihat spion masa
silam urang Sunda, menuju pergerakan jaman. Tinggal apakah masa lalu sunda itu
merupakan sekadar panineungan atawa
bayangbayang yang senantiasa mengikuti modernitas?
Buku itu menjawab pertanyaan di atas
dengan menghadapkan pembaca pada sebuah jaman modern yang berbicara tentang
kelupaan pada arah jalan pulang menuju lemah
cai, yang ketika sampai ke padanya, justru batas antara desa dan kota sudah
semakin nirzona oleh serangan modernitas yang menafikan kemanusiaan,
kenyataannya pada gugus desa pun tengah berlangsung keruntuhan nilai itu,
seperti halnya tragedi kemanusiaan dukun santet di sebuah desa dalam Kalapati (hal 45) dan berbagai konflik
sosial (Kalakay, Kampung Samada, dan
lemah Cai Kulup).
Namun semangat Hadi dalam melukiskan
dekadensi moral itu adalah semacam eksperimentasi bahwa pada dasarnya kebenaran
yang digadang-gadang mampu menyelesaikan berbagai persoalan hidup mendapatkan
maknanya dari sesuatu yang mendistorsi dirinya sendiri: Kriminalitas dan segala
prilaku abnormalitas manusia dan hal itu semakin terasa dalam kisah-kisah lain
(Kembang Pati, Kalangkang Bulan dan
Anaking Jeung Bulan) yang tak bisa semua disampaikan di sini karena
terbatasnya ruang.
***
Cikarang, 26 Agustus 2012
*Kalapati,
Kumpulan Carpon Hadi AKS, Nomor: 411/KBUG/2012. Kiblat Buku Utama Citakan
ka1, Rabiul Awal 1433 H./ Februari 2012